Pada artikel sebelumnya disini, kita sudah sedikit mengupas mengenai pentingnya Nilai Buku per Lembar Saham/BVPS (Ekuitas/Jumlah lembar saham) dalam mencari nilai intrinsik sebuah saham. Metode menghitung BVPS ini dikenal juga dengan istilah Net Assets Value (NAV). Metode ini pertama sekali diperkenalkan oleh Benjamin Graham, seorang profesor di Columbia University pada tahun 1934. Menimbang tahunnya, metode ini tergolong old-school dan sangat konservatif, tapi tidak ada salahnya kita sedikit mengupas latar belakang dari metode NAV ini dan sosok yang memperkenalkan metode ini yang hingga sekarang masih dianut oleh kebanyakan para deep-value investor.
1. Net Assets Value (NAV)
Bagi Anda penganut paham Value-Investing seharusnya mengetahui Mr. Graham ini, terlebih ia dikenal sebagai "Guru" dari Super Investor Warren Buffett. Mr. Graham dikenal melalui bukunya Security Analysis, yang diterbitkan bersama dengan rekannya yang juga seorang profesor di Columbia University David Dodd. Kemudian Mr. Graham menerbitkan buku keduanya pada 1949 yang berjudul The Intelligent Investor, dan kedua buku ini masih sangat relevan hinggat saat ini dan sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai Value Investing sehingga masih dicetak dan dijual meskipun sudah berumur hampir 100 tahun sejak diterbitkan pertama kali.
Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Mr. Graham juga adalah seorang investor. Pada tahun 1926 Mr. Graham membentuk sebuah investment partnership bersama dengan Jerome Newman (partnership ini yang kelak hampir 30 tahun kemudian mempekerjakan Warren Buffett muda). Seandainya kita membandingkan kondisi pasar saham dan ekonomi ketika itu dibandingkan masa sekarang, maka masa sebelum 1950an tersebut terasa jauh lebih berat karena banyak perang seperti Perang Dunia II, Perang Korea, dan juga pertama kalinya terjadi Wall Street Crash (Black Tuesday) pada 1929 yang banyak membuat para investor Wall Street bangkrut. Tetapi hebatnya, Graham-Newman Partnership bertahan hingga akhirnya Mr. Graham pensiun pada 1956.
Bagaimana cara Graham-Newman bertahan? Mr. Graham menuliskan semua metode dan pemahamannya di dalam buku Security Analysis yang terbit beberapa tahun setelah Wall Street Crash yang diiringi dengan The Great Depression yang terjadi hingga sepanjang dekade 1930an berakhir. Intinya, Mr. Graham memperkenalkan suatu metode yang benar-benar bisa dianggap sebagai sebuah investasi dibandingkan spekulasi dengan cara menerapkan Margin of Safety.
Prinsip ini merupakan kunci bagi para investor untuk bisa bertahan dalam berbagai resiko ekonomi dan resesi yang mungkin terjadi. Setelah menghitung aset bersih dari suatu saham, maka paling tidak seorang investor harus membeli saham tersebut pada harga paling tidak 25% lebih rendah dari nilai aset bersihnya. Sebagai contoh, apabila suatu saham memiliki nilai BVPS 100 per lembar saham, maka seorang investor boleh membeli saham tersebut dengan harga < 75 per lembar saham. Inilah yang disebut oleh Mr. Graham sebagai margin of safety.
Apabila seorang investor menerapkan prinsip ini, maka seandainya terjadi resesi dan perusahaan tersebut bangkrut hingga kemudian aset-asetnya dilelang, maka paling tidak si investor tadi mendapatkan nilai aset yang harganya 100 per lembar tadi sehingga masih memberikan margin keuntungan 25%.
Metode ini bagi kebanyakan orang terlihat sangat membosankan, "main aman", dan sangat tidak sophisticated, dibandingkan dengan analisis-analisis para trader teknikal dengan istilah keren seperti support, resistance, rebound ataupun nama-nama pola teknikal keren seperti three crows zero, marubozu dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya ada banyak Super Investor terlahir dari prinsip ini.
Mr. Graham ketika mengajar prinsip finance dan investment pada kelas malam di Columbia University, memiliki murid-murid yang terdiri dari para mahasiswa hingga para profesional dan investor yang tertarik mengikuti kelas yang diajarkan oleh Mr. Graham. Diantara kelas-kelas yang diajarnya, ia memiliki murid seperti Warren Buffett, dan Bill Ruane. Ketika ia membentuk Graham-Newman Partnership, ia merekrut Walter Schloss, Tom Knapp, dan juga Bill Ruane hingga Warren Buffet sendiri. Dan masing-masing muridnya ini kelak membentuk perusahaan investasi sendiri dan menjadi Super Investor dengan basis pemahaman deep-value investing yang diperoleh dari Mr. Graham.
Bisa dibilang metode ini tahan banting dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, tetapi diperlukan kesabaran agar metode ini benar-benar memberikan keuntungan bagi para investor. Dan banyak profesional dan para value investor masa sekarang beranggapan prinsip Mr. Graham ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena perkembangan teknologi dan perubahan situasi ekonomi sekarang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 1920an. Dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, investor sangat mudah untuk mendapatkan laporan keuangan suatu perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan undervalued sangat mudah ditemukan. Akibatnya kebanyakan saham-saham tersebut harganya sudah terdongkrak naik duluan. Selain itu, kebijakan-kebijakan, undang-undang, serta perlindungan hukum bagi perusahaan-perusahaan sudah sangat komprehensif , sehingga apabila suatu perusahaan bangkrut, proses untuk lelang aset perusahaan akan sangat merepotkan dan memakan waktu lama, terlebih lagi apabila perusahaan tersebut telah mengajukan perlindungan pailit terlebih dahulu, seorang investor harus berlapang dada merelakan uangnya "tenggelam" lebih lama atau bahkan bisa-bisa tidak balik lagi.
Terlepas dari anggapan tersebut, faktanya, prinsip deep-value investing seperti yang diajarkan Mr. Graham memberikan pemahaman bagi para investor terhadap nilai intrinsik suatu perusahaan (yang tangible tentunya seperti yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan) berdasarkan aset bersihnya dan betapa pentingnya menerapkan konsep Margin of Safety dalam menentukan "harga aman" ketika seorang investor hendak berinvestasi di suatu perusahaan. Prinsip MoS ini pula kelak yang selalu diterapkan oleh Warren Buffet dalam "menyaring" perusahaan-perusahaan yang hendak dibelinya melalui Berkshire Hathaway. Apabila Mr. Buffet menemukan good companies yang lolos kriterianya tetapi harganya di pasar tidak memenuhi prinsip MoS, maka ia akan menunda pembelian perusahaan tersebut hingga harganya sesuai, atau mungkin malah mencari perusahaan yang lain (kita nanti akan membahas kriteria good companies Mr. Buffett di artikel dengan judul yang berbeda, sedangkan metode valuasi yang diterapkan Mr. Buffett dalam menentukan harga wajar suatu perusahaan akan kita bahas pada lanjutan artikel ini).
Sesuai dengan kalimat yang selalu diucapkannya,
"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price".
Sesuai dengan kalimat yang selalu diucapkannya,
"It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price".
Kesimpulan dari metode NAV ini adalah bahwa nilai intrinsik dari suatu perusahaan adalah nilai aset bersih (ekuitas) perusahaan tersebut. Dan karena perusahaan membagi asetnya berdasarkan banyak lembar saham yang disetor penuh, maka nilai intrinsik dari suatu perusahaan adalah Ekuitas/Jumlah lembar saham (BVPS). Apabila BVPS sebuah saham adalah 100, dan di pasar sahamnya diperdagangkan dengan harga 75, maka PBV dari saham ini adalah 0,75. Dengan berpatokan pada prinsip margin of safety, maka ini adalah harga aman untuk membeli saham tersebut. Lebih rendah tentu lebih baik.
Prinsip ini diterapkan oleh Warren Buffet pada masa awal-awal sebelum ia memiliki Berkhsire Hathaway, dimana ia membentuk suatu partnership dengan mengumpulkan dana dari keluarga dan kerabat dekatnya dengan total dana awal sebesar $100.500. Buffet Partnership ketika itu menerapkan prinsip yang disebut oleh Mr. Buffett sendiri dengan istilah Cigar Butt. Mr. Buffett membeli saham-saham yang sangat murah dengan nilai Pbv bahkan di bawah 0,5 yang kebanyakan terdiri dari saham-saham perusahaan yang berada di akhir-akhir masanya tanpa memperhatikan fundamental perusahaan sama sekali. Tetapi anehnya, tidak banyak dari perusahaan ini yang pada akhirnya benar-benar bangkrut, dan perusahaan yang ternyata kemudian benar-benar bangkrut pun memiliki suatu masa dimana harga sahamnya justru sempat naik sebelum akhirnya benar-benar habis. Mirip seperti ujung-ujung sisa rokok yang habis dalam dua atau tiga kali hisap, dan oleh karena itu dinamakan Cigar Butt oleh Mr. Buffett.
2. Peter Lynch's Fair P/E Ratio
Apabila Anda pernah menghitung nilai buku (BVPS) dari beberapa saham-saham bluechip (dan bahkan mungkin saham-saham second-liner) di Indonesia, Anda mungkin akan menyadari kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut justru malah memiliki Pbv jauh lebih besar daripada 1. Lalu berapa lama kita harus menunggu agar harga dari saham-saham bluechip itu lebih rendah dari nilai asetnya?
Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di artikel ini, harga saham perusahaan tersebut jauh lebih besar dari nilai aset bersihnya karena adanya ekspektasi terhadap perusahaan tersebut. Ekspektasinya dapat berupa pertumbuhan pendapatan yang diyakini investor mampu diwujudkan oleh perusahaan tersebut, atau mungkin karena nama brand yang telah begitu melekat di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, permasalahan dari mencari harga wajar suatu perusahaan menggunakan nilai aset bersihnya adalah, komponen NAV ini tidak memperdulikan besarnya pendapatan yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi bisa dibayangkan, apabila Anda menggunakan NAV sebagai standar harga yang harus Anda dapatkan ketika Anda mau membeli Unilever, mungkin hingga 20 atau 30 tahun lagi belum tentu Anda akan mendapatkan harga saham Unilever senilai dengan aset bersihnya.
Berbeda dengan Mr. Graham yang cenderung lebih suka menerapkan nilai aset untuk mendapatkan harga wajar suatu perusahaan, salah seorang Investor Amerika terkenal lainnya, Peter Lynch, justru lebih menyukai pendekatan Price to Earning Ratio. Argumentasi dari Mr. Lynch adalah bahwa harga saham suatu perusahaan justru seharusnya sangat bergantung terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Apabila pendapatan perusahaan naik dari tahun ke tahun, harga sahamnya lambat laun akan mengikuti kenaikan harga saham tersebut, vice versa.
Rule of thumb yang digunakan oleh Peter Lynch adalah sebagai berikut:
Fair P/E = Earnings Growth Rate (Long-term rate, without %)
Maksudnya adalah apabila laba bersih suatu perusahaan tumbuh 20% dari tahun lalu, maka nilai Price to Earning Ratio-nya adalah 20 kali. Sebagai contoh, laba bersih perusahaan A dalam setahun adalah 100 juta, dan jumlah lembar saham disetor penuh sebanyak 1 juta, maka EPS (Earning per Share) perusahaan A adalah 100. Apabila sejak 10 tahun terakhir laba perusahaan A rata-ratatumbuh 20%, maka nilai P/E ideal perusahaan A adalah 20, sehingga harga wajar dari saham perusahaan A yaitu 20*100 = 2000. Seandainya di pasar perusahaan A dihargai di bawah 2000, maka perusahaan A tergolong undervalue, dan sebaliknya.
Ada dua hal yang perlu digaris-bawahi dari metode Peter Lynch di atas. Pertama, beberapa investor ternama lebih menyukai menggunakan rata-rata pertumbuhan EBITDA dibandingkan rata-rata pertumbuhan laba bersih. Hal ini dikarenakan EBITDA dipandang lebih tepat dalam merefleksikan pertumbuhan yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan, tanpa perlu melibatkan perhitungan-perhitungan akuntansi yang sifatnya hanya di atas kertas seperti amortisasi, depresiasi, dan beban pajak serta beban keuangan yang tidak terkait dengan kemampuan operasional perusahaan.
Kedua, metode perhitungan Peter Lynch di atas hanya cocok untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil. Metode ini tidak cocok untuk perusahaan yang sifat bisnisnya cyclical (siklus) seperti perusahaan pertambangan dan penghasil komoditas bahan mentah lainnya dimana perusahaan tersebut di beberapa tahun mampu mendapatkan untung besar yang disebabkan oleh naiknya harga batubara atau harga minyak, dan di tahun-tahun berikutnya mungkin malah menderita kerugian karena harga komoditas tersebut anjlok.
Dan sejauh pengamatan penulis, rata-rata perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, justru bersifat cyclical, alias tren pertumbuhan laba bersihnya tidak menentu sehingga metode ini kurang cocok diterapkan di kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan blue chip yang rutin membukukan pertumbuhan laba, Anda dapat menerapkan pendekatan ini untuk menentukan harga wajar sebuah perusahaan.
Median P/E Ratio
Disebut dengan Peter Lynch's chart, tetapi sebenarnya dipopulerkan kemudian oleh Charlie Tian, investor dan juga pemiliki GuruFocus.com. Chart ini membantu para investor untuk memahami nilai wajar suatu perusahaan berdasarkan historikal P/E rationya. Caranya yaitu dengan mencari nilai tengah dari P/E ratio suatu perusahaan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (rentang waktu yang disarankan oleh Charlie Tian).
Nilai median dari P/E ratio yang didapatkan kemudian digambarkan berupa garis yang disebut earnings line dan berdampingan dengan garis harga saham 10 tahun terakhir. Sebagai contoh, setelah mencari nilai tengah P/E ratio perusahaan B 10 tahun terakhir didapatkanlah angka Median P/E Ratio sebesar 20. Earnings line dibentuk dengan mengalikan EPS perusahaan di suatu periode dengan angka 20 ini, dan begitu seterusnya hingga periode 10 tahun dengan faktor pengali tetap 20.
Sebagai contoh, kita gunakan grafik yang dibuat oleh Charlie Tian dengan menghitung median P/E dari perusahaan CVS health di US (*gambar diperoleh dari buku Invest Like A Guru. Charlie Tian).
Setelah mencari nilai P/E CVS Corp sejak tahun 1995 hingga 2017, diperoleh nilai median P/E sebesar 18.6. Maksudnya adalah, sejak 1995 hingga 2017, harga saham dari CVS Corp bergerak tidak jauh dari nilai P/E ratio sebesar 18,6 kali. Dan apabila digambarkan ke dalam grafik, maka dapat diperhatikan bahwa harga saham CVS (warna merah) tergolong undervalue apabila berada di bawah garis earnings line (warna biru), dan tergolong overvalue apabila berada di atas garis earnings line.
Jujur saja, penulis sendiri jarang sekali menggunakan metode Median P/E chart ini dalam menilai harga wajar suatu perusahaan dikarenakan jauhnya range data yang digunakan hingga 10 tahun terakhir sehingga memerlukan effort yang luar biasa dalam membuat grafiknya. Belum lagi ketersediaan data karena pengarsipan data digital di BEI belum sebagus di NYSE sana.
Tapi penulis beberapa kali menggunakan metode nilai tengah/median, bukan dengan menggunakan P/E melainkan menggunakan P/S, yaitu price sales ratio. Metode ini juga diperkenalkan oleh Charlie Tian, pertimbangannya karena kebanyakan perusahaan jarang sekali memiliki pertumbuhan laba bersih yang stabil sehingga memberikan distorsi yang besar pada nilai median P/E, sehingga P/E diganti dengan nilai Total Penjualan Perusahaan (yang biasanya lebih stabil) dibagi dengan jumlah saham beredar untuk kemudian dicari nilai mediannya (itupun penulis hanya mencari data historis maksimal 4 tahun terakhir).
Selain itu, dengan menggunakan Peter Lynch Fair P/E Ratio ataupun Median P/E Ratio, maka asumsi kita terfokus sepenuhnya ke masa lalu, bukan potensi perusahaan ke depan. Oleh karena itu, penulis sendiri lebih sering menggunakan 2 metode yang akan kita bahas pada artikel berikutnya, yaitu metode Discounted Owner's Earning yang dipopulerkan oleh Warren Buffett, dan Fair P/BV Ratio yang merupakan penggabungan prinsip dari Warren Buffet dan juga adaptasi prinsip Rule of Thumb yang diperkenalkan oleh Peter Lynch di atas.
Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di artikel ini, harga saham perusahaan tersebut jauh lebih besar dari nilai aset bersihnya karena adanya ekspektasi terhadap perusahaan tersebut. Ekspektasinya dapat berupa pertumbuhan pendapatan yang diyakini investor mampu diwujudkan oleh perusahaan tersebut, atau mungkin karena nama brand yang telah begitu melekat di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, permasalahan dari mencari harga wajar suatu perusahaan menggunakan nilai aset bersihnya adalah, komponen NAV ini tidak memperdulikan besarnya pendapatan yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi bisa dibayangkan, apabila Anda menggunakan NAV sebagai standar harga yang harus Anda dapatkan ketika Anda mau membeli Unilever, mungkin hingga 20 atau 30 tahun lagi belum tentu Anda akan mendapatkan harga saham Unilever senilai dengan aset bersihnya.
Berbeda dengan Mr. Graham yang cenderung lebih suka menerapkan nilai aset untuk mendapatkan harga wajar suatu perusahaan, salah seorang Investor Amerika terkenal lainnya, Peter Lynch, justru lebih menyukai pendekatan Price to Earning Ratio. Argumentasi dari Mr. Lynch adalah bahwa harga saham suatu perusahaan justru seharusnya sangat bergantung terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Apabila pendapatan perusahaan naik dari tahun ke tahun, harga sahamnya lambat laun akan mengikuti kenaikan harga saham tersebut, vice versa.
Rule of thumb yang digunakan oleh Peter Lynch adalah sebagai berikut:
Fair P/E = Earnings Growth Rate (Long-term rate, without %)
Maksudnya adalah apabila laba bersih suatu perusahaan tumbuh 20% dari tahun lalu, maka nilai Price to Earning Ratio-nya adalah 20 kali. Sebagai contoh, laba bersih perusahaan A dalam setahun adalah 100 juta, dan jumlah lembar saham disetor penuh sebanyak 1 juta, maka EPS (Earning per Share) perusahaan A adalah 100. Apabila sejak 10 tahun terakhir laba perusahaan A rata-ratatumbuh 20%, maka nilai P/E ideal perusahaan A adalah 20, sehingga harga wajar dari saham perusahaan A yaitu 20*100 = 2000. Seandainya di pasar perusahaan A dihargai di bawah 2000, maka perusahaan A tergolong undervalue, dan sebaliknya.
Ada dua hal yang perlu digaris-bawahi dari metode Peter Lynch di atas. Pertama, beberapa investor ternama lebih menyukai menggunakan rata-rata pertumbuhan EBITDA dibandingkan rata-rata pertumbuhan laba bersih. Hal ini dikarenakan EBITDA dipandang lebih tepat dalam merefleksikan pertumbuhan yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan, tanpa perlu melibatkan perhitungan-perhitungan akuntansi yang sifatnya hanya di atas kertas seperti amortisasi, depresiasi, dan beban pajak serta beban keuangan yang tidak terkait dengan kemampuan operasional perusahaan.
Kedua, metode perhitungan Peter Lynch di atas hanya cocok untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil. Metode ini tidak cocok untuk perusahaan yang sifat bisnisnya cyclical (siklus) seperti perusahaan pertambangan dan penghasil komoditas bahan mentah lainnya dimana perusahaan tersebut di beberapa tahun mampu mendapatkan untung besar yang disebabkan oleh naiknya harga batubara atau harga minyak, dan di tahun-tahun berikutnya mungkin malah menderita kerugian karena harga komoditas tersebut anjlok.
Dan sejauh pengamatan penulis, rata-rata perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, justru bersifat cyclical, alias tren pertumbuhan laba bersihnya tidak menentu sehingga metode ini kurang cocok diterapkan di kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagi perusahaan-perusahaan blue chip yang rutin membukukan pertumbuhan laba, Anda dapat menerapkan pendekatan ini untuk menentukan harga wajar sebuah perusahaan.
Median P/E Ratio
Disebut dengan Peter Lynch's chart, tetapi sebenarnya dipopulerkan kemudian oleh Charlie Tian, investor dan juga pemiliki GuruFocus.com. Chart ini membantu para investor untuk memahami nilai wajar suatu perusahaan berdasarkan historikal P/E rationya. Caranya yaitu dengan mencari nilai tengah dari P/E ratio suatu perusahaan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (rentang waktu yang disarankan oleh Charlie Tian).
Nilai median dari P/E ratio yang didapatkan kemudian digambarkan berupa garis yang disebut earnings line dan berdampingan dengan garis harga saham 10 tahun terakhir. Sebagai contoh, setelah mencari nilai tengah P/E ratio perusahaan B 10 tahun terakhir didapatkanlah angka Median P/E Ratio sebesar 20. Earnings line dibentuk dengan mengalikan EPS perusahaan di suatu periode dengan angka 20 ini, dan begitu seterusnya hingga periode 10 tahun dengan faktor pengali tetap 20.
Sebagai contoh, kita gunakan grafik yang dibuat oleh Charlie Tian dengan menghitung median P/E dari perusahaan CVS health di US (*gambar diperoleh dari buku Invest Like A Guru. Charlie Tian).
Setelah mencari nilai P/E CVS Corp sejak tahun 1995 hingga 2017, diperoleh nilai median P/E sebesar 18.6. Maksudnya adalah, sejak 1995 hingga 2017, harga saham dari CVS Corp bergerak tidak jauh dari nilai P/E ratio sebesar 18,6 kali. Dan apabila digambarkan ke dalam grafik, maka dapat diperhatikan bahwa harga saham CVS (warna merah) tergolong undervalue apabila berada di bawah garis earnings line (warna biru), dan tergolong overvalue apabila berada di atas garis earnings line.
Jujur saja, penulis sendiri jarang sekali menggunakan metode Median P/E chart ini dalam menilai harga wajar suatu perusahaan dikarenakan jauhnya range data yang digunakan hingga 10 tahun terakhir sehingga memerlukan effort yang luar biasa dalam membuat grafiknya. Belum lagi ketersediaan data karena pengarsipan data digital di BEI belum sebagus di NYSE sana.
Tapi penulis beberapa kali menggunakan metode nilai tengah/median, bukan dengan menggunakan P/E melainkan menggunakan P/S, yaitu price sales ratio. Metode ini juga diperkenalkan oleh Charlie Tian, pertimbangannya karena kebanyakan perusahaan jarang sekali memiliki pertumbuhan laba bersih yang stabil sehingga memberikan distorsi yang besar pada nilai median P/E, sehingga P/E diganti dengan nilai Total Penjualan Perusahaan (yang biasanya lebih stabil) dibagi dengan jumlah saham beredar untuk kemudian dicari nilai mediannya (itupun penulis hanya mencari data historis maksimal 4 tahun terakhir).
Selain itu, dengan menggunakan Peter Lynch Fair P/E Ratio ataupun Median P/E Ratio, maka asumsi kita terfokus sepenuhnya ke masa lalu, bukan potensi perusahaan ke depan. Oleh karena itu, penulis sendiri lebih sering menggunakan 2 metode yang akan kita bahas pada artikel berikutnya, yaitu metode Discounted Owner's Earning yang dipopulerkan oleh Warren Buffett, dan Fair P/BV Ratio yang merupakan penggabungan prinsip dari Warren Buffet dan juga adaptasi prinsip Rule of Thumb yang diperkenalkan oleh Peter Lynch di atas.
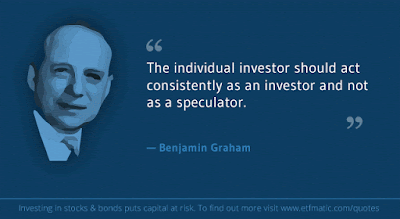

Pertamax
ReplyDelete